Majelis Ulama Indonesia (JIL), dalam fatwanya yang tegas-tegas menyatakan keharaman mengikuti ideologi sekularisme, pluralisme dan liberalisme, mendefinisikan pluralisme sebagai berikut:
...suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh karena itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah.
Fatwa ini kemudian mendapat tanggapan sangat keras, bahkan cemoohan, dari kalangan pluralis. Setelah fatwa tersebut dikeluarkan, aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL) menuliskan sanggahannya. Anehnya, mereka memprotes MUI justru karena lembaga ini telah memberikan suatu definisi yang baku terhadap pluralisme. Sebaliknya, mereka bersikeras untuk membiarkan pluralisme sebagai sebuah ideologi yang belum disepakati definisinya.
Sayang sekali, semua definisi yang diajukan oleh kalangan pluralis di atas tidaklah tegas, sehingga justru menurunkan nilai ilmiah dari ideologi pluralisme itu sendiri. Definisi-definisi yang mereka berikan gagal menjawab dua pertanyaan berikut: (1) atas dasar pemikiran apa kita bersikap toleran dan saling menghormati, dan (2) bagaimana cara kita mewujudkannya?
Jika yang ditawarkan oleh konsep pluralisme hanyalah toleransi atau saling menghormati, maka tidak akan terjadi banyak perdebatan, bahkan bisa dipastikan semua ulama akan segera membenarkannya. Di sisi lain, jika memang hanya demikian, maka istilah “pluralisme” sendiri menjadi mubadzir, karena sudah terwakili dengan istilah “toleransi”. Untuk memahami kandungan yang sebenarnya dari konsep pluralisme itu sendiri, dua pertanyaan di atas memang sangat perlu untuk diajukan. Malah, jawaban dari kedua pertanyaan itulah yang bisa menunjukkan alasan penolakan umat Islam terhadap pluralisme.
Pertama, dasar pemikiran dari sikap toleran yang diajarkan oleh pluralisme adalah penyamarataan agama. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh MUI, dalam setiap pemikiran pluralisme, setiap agama ditempatkan pada posisi yang sejajar.
Tuhan memiliki banyak nama?Memang pemikiran pluralisme itu sendiri memiliki berbagai corak atau tren. Sebagian kalangan pluralis mengajukan tawaran yang murni sekuler demi menjaga keharmonisan antar umat beragama. Menurut kalangan ini, agama harus dicegah dari ruang publik, diatur oleh akal manusia, dan tidak memiliki otoritas sama sekali dalam sistem sosial kemasyarakatan. Sebagian lainnya mengatakan bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama, meskipun ritualnya berbeda-beda. Yang lainnya lagi mengatakan bahwa semua agama itu sama-sama benar, sekaligus juga sama-sama mengandung kesalahan. Oleh karena itu, yang baik boleh diambil, sedangkan yang salah harus ditinggalkan. Ada juga yang mengatakan bahwa masing-masing agama sudah benar, dan semua agama sama pada level batiniah (esoterik), sehingga tak perlu disekulerkan. Akan tetapi, pada akhirnya solusi inipun mengarah pada sekularisme. Karena tak ada agama yang boleh mengklaim paling benar, maka lagi-lagi kekuasaan diberikan pada pemerintahan sekuler. Ada juga kalangan Teosofi yang menganggap semua agama benar, bahkan mereka meramu unsur-unsur mistis yang menurutnya bisa ditemukan dalam semua ajaran agama.
Pada akhirnya, pluralisme memang berdiri pada tonggak penyamarataan agama. Semua agama sama, meskipun kesamaannya berbeda-beda; sama-sama tunduk pada akal manusia, sama-sama menyembah Tuhan yang Satu, sama-sama benar dan sama-sama salah, sama pada level esoteriknya, atau sama-sama mewariskan peninggalan ajaran-ajaran mistis.
Masalah kedua adalah pada cara mewujudkan toleransi itu sendiri berdasarkan paham pluralisme. Toleransi adalah konsep yang sudah dipahami dan dijunjung tinggi oleh kalangan ulama. Akan tetapi, jika toleransi itu diwujudkan dengan menggelar doa bersama, atau perayaan hari raya bersama, maka hal itu telah melanggar batas. Kalangan ulama sejak jauh-jauh hari telah menjelaskan bahaya bercampuraduknya aqidah dalam kegiatan-kegiatan yang semacam ini.
Toleransi juga tidak dibenarkan jika harus mengakibatkan terjualnya aqidah, meski hanya dengan sekedar pengakuan saja. Sebagai contoh, seorang Muslim tidak boleh membenarkan agama Kristen, karena agama Kristen menolak status Rasulullah saw. sebagai Nabi Terakhir, sedangkan agama Islam sendiri (berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah) telah terang-terangan menunjukkan poin-poin kesalahan dalam ajaran Kristen.
Anehnya, ayat yang kerap digunakan sebagai pembenaran oleh kalangan pluralis justru merupakan ayat yang tegas-tegas menolak pluralisme itu sendiri. Dalam berbagai argumennya, kalangan pluralis seringkali mengutip ayat terakhir dalam Surah Al-Kaafiruun (“lakum diinukum wa liyadiin”). Padahal, sebagaimana telah dijelaskan dalam berbagai kitab Sirah Nabawiyah, konteks turunnya Surah Al-Kaafiruun adalah penolakan Islam terhadap tawaran kaum musyrikin Mekkah yang meminta Rasulullah saw. dan para pengikutnya mau menyembah berhala-berhala mereka, sedangkan mereka pun siap menyembah Allah SWT sebagaimana Rasulullah saw. dan para pengikutnya. Maka turunlah Surah Al-Kaafiruun yang menyatakan bahwa Islam dan ajaran kemusyrikan tidaklah sama, dan selamanya takkan bisa digabungkan.
Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan lebih lanjut tentang makna penolakan dalam surah Al-Kaafiruun ini, juga mengutip tafsiran Ibnu Katsir dan Muhammad ‘Abduh. Menurutnya, dalam surah ini tidak hanya ditegaskan bahwa yang disembah oleh umat Islam tidaklah sama dengan berhala-berhala itu, namun juga dijelaskan bahwa cara-cara peribadatannya pun berbeda. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti doa bersama tidak dapat dibenarkan, karena yang diseru oleh masing-masing umat beragama itu berbeda, dan caranya pun berbeda-beda, sehingga tak mungkin dipersatukan. Bagi umat Islam, tak mungkin mempersatukan yang haq dan yang bathil.
Dalam perkembangannya kini, paham pluralisme pun dijadikan pembenaran untuk membela aliran-aliran sesat, karena umumnya orang-orang pluralis menganggap agama sebagai suatu hal yang sifatnya pribadi dan tak boleh dicampuri oleh siapa pun. Kalangan pluralis membela agama Lia Eden dan Ahmadiyah, antara lain dengan menggunakan kaidah “lakum diinukum wa liyadiin” itu pula. Terlihat jelas bahwa para pengusung pluralisme tidak memiliki basis yang kuat dalam ilmu tafsir Qur’an, sehingga ayat terakhir dalam Surah Al-Kaafiruun tersebut ditafsirkan tanpa mempertimbangkan hubungannya dengan lima ayat sebelumnya dan konteks asbabun nuzul-nya.
Meski demikian, banyak dari kalangan pluralis yang didaulat menjadi “ahli ilmu tafsir Qur’an”. Salah satunya adalah Abd. Moqsith Ghazali yang memperoleh gelar doktornya dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam bukunya (yang dikembangkan dari disertasinya) yang berjudul Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an, Moqsith menyertakan sebuah subbab yang diberi judul “Kajian Pluralisme Belum Kukuh”. Ironisnya, buku itu pun pada akhirnya tidak memberikan definisi yang tegas untuk pluralisme itu sendiri. Dengan kata lain, disertasi Moqsith telah gagal menjawab pertanyaan yang diajukannya sendiri.
Kita dapat melihat dengan jelas bahwa definisi yang diberikan oleh MUI ternyata cukup memuaskan dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam definisi tersebut tergambar dasar pemikiran pluralisme agama (yaitu pandangan bahwa semua agama sama), sekaligus juga konsekuensi dari pluralisme yang tidak dapat dibenarkan oleh Islam (yaitu penolakan klaim kebenaran oleh agama manapun). Kalangan pluralis seharusnya berterima kasih atas pengajuan definisi yang demikian. Paling tidak, mereka bisa mencontoh MUI bagaimana memberikan batasan atas sebuah wacana ilmiah sebelum memutuskan untuk memperdebatkannya, apalagi memasukkannya dalam kurikulum pendidikan.













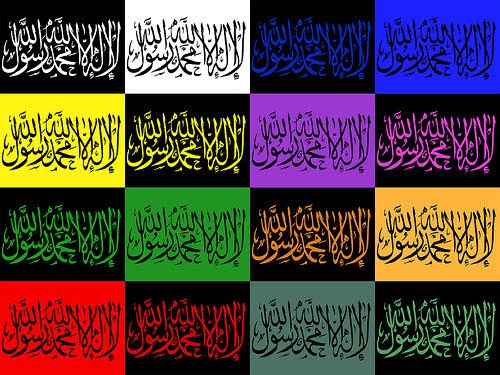









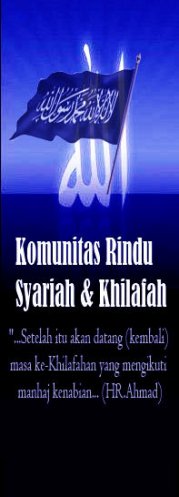





0 komentar:
Posting Komentar